BUMDes, Cerita Tak Berjudul di Tengah Lahirnya Kopdes Merah Putih
Oleh: Mulyadi
Pemimpin Redaksi KabarGEMPAR.com
BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) sempat digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi perdesaan. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal melalui prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Namun seiring waktu, eksistensi BUMDes mulai kehilangan arah. Program-programnya tak jarang hanya menyisakan jejak tanpa hasil konkret. Kini, posisinya perlahan mulai tergeser oleh entitas baru bernama Koperasi Desa Merah Putih.
Kopdes Merah Putih, dibentuk melalui Keputusan Presiden dan diluncurkan secara serentak di sejumlah wilayah, hadir dengan narasi besar: memperkuat ekonomi rakyat. Tak tanggung-tanggung, modal awal yang digelontorkan mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi. Beberapa menteri disebut menjadi “bidan” dalam kelahirannya. Namun muncul satu pertanyaan mendasar: benarkah koperasi ini lahir dari kehendak rakyat atau hanya buah dari kehendak kekuasaan?
Secara filosofis, koperasi adalah wadah ekonomi yang lahir dari bawah, dari kebutuhan bersama masyarakat yang ingin maju secara kolektif. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun berbeda dengan koperasi konvensional, Kopdes Merah Putih justru lahir dari atas, “top-down”, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai legitimasi sosial dan keberlanjutan organisasinya.
Di banyak desa, kemunculan Kopdes Merah Putih memunculkan dinamika baru. Persoalan klasik pun kembali muncul: siapa yang berhak menduduki jabatan dalam struktur organisasi? Siapa yang paling pantas mengelola dana miliaran rupiah tersebut? Pro-kontra pun tak terelakkan, bahkan memunculkan gesekan sosial di akar rumput.
Sementara itu, BUMDes yang sejak awal dibentuk melalui musyawarah desa justru banyak yang stagnan. Data dari
Kemendes dan BPK menunjukkan sebagian besar BUMDes belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian desa. Banyak yang hanya menjadi “pajangan administrasi” tanpa aktivitas usaha yang nyata. Ibarat cerita tanpa judul, tak jelas arah, tak terlihat hasilnya.
Ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Jika pendekatan kekuasaan tetap menjadi cara utama membentuk lembaga ekonomi rakyat, maka risiko kegagalan akan berulang. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat, dana besar hanya akan menguap seperti yang terjadi pada banyak BUMDes. Ironisnya, justru masyarakat desa yang akan menanggung dampaknya.
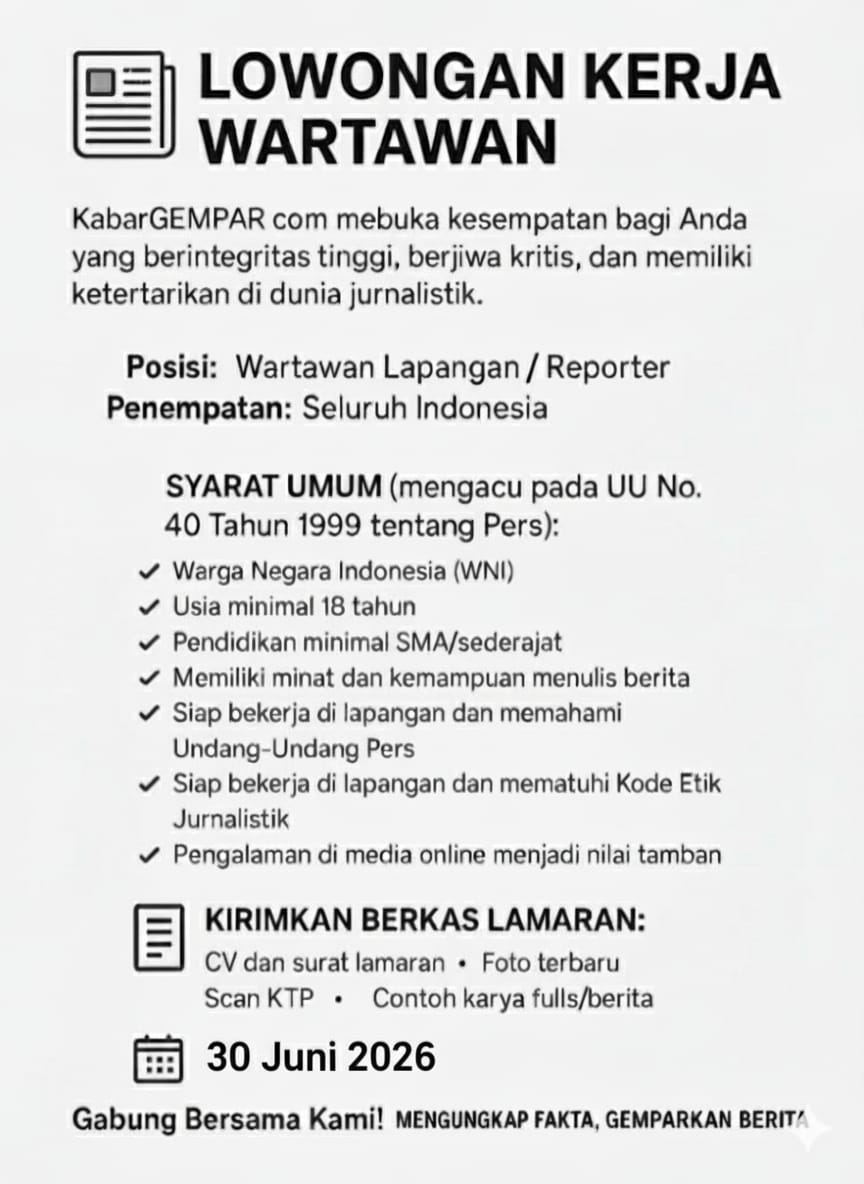
Evaluasi menyeluruh menjadi keharusan. Pemerintah pusat perlu berhati-hati agar program Kopdes Merah Putih tidak menjadi bayang-bayang kegagalan yang sama. Lembaga ekonomi rakyat harus dibangun bukan karena proyek kekuasaan, melainkan karena kebutuhan riil masyarakat. Dan selama mentalitas kepemimpinan desa belum bertransformasi dari korup menjadi solutif, program sehebat apapun hanya akan jadi santapan segelintir elite lokal.
- BUMDes dan Kopdes Merah Putih
- BUMDes stagnan tanpa arah
- Ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat
- Evaluasi BUMDes di Indonesia
- Koperasi Desa Merah Putih top-down
- Kritik terhadap program Kopdes
- Legitimasi sosial koperasi desa
- Permasalahan dana desa miliaran
- Reformasi kepemimpinan desa
- Risiko kegagalan ekonomi desa



