Jakarta: Dari Pelabuhan Kuno ke Jantung Republik
Oleh: Mulyadi
Dipublikasikan: 14 Juni 2025
JAKARTA, kota megapolitan yang kini menjadi pusat denyut nadi Indonesia, menyimpan sejarah panjang yang kaya akan dinamika kekuasaan, perdagangan, dan perjuangan. Menjelang usianya yang ke-498 pada Juni 2025, Jakarta bukan hanya sekadar pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga saksi bisu berbagai babak penting dalam sejarah bangsa. Sebagai warga negara yang hidup di zaman modern, mengenal kembali sejarah Jakarta berarti menggali akar dari identitas nasional kita, dan memahami bagaimana masa lalu membentuk wajah kota yang kita kenal hari ini.
Sunda Kelapa: Awal Sebuah Pelabuhan yang Strategis
Sebelum dikenal dengan nama Jakarta, wilayah ini dahulu disebut Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan yang sudah berfungsi sejak abad ke-5. Pelabuhan ini menjadi bagian vital dari jaringan perdagangan kerajaan Hindu-Buddha seperti Tarumanegara dan kemudian Kerajaan Sunda. Letaknya yang berada di muara sungai Ciliwung menjadikannya pelabuhan ideal bagi kapal-kapal dagang dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Aktivitas ekonomi berlangsung ramai; dari rempah-rempah, kain sutra, hingga keramik menjadi komoditas pertukaran.
Pentingnya Sunda Kelapa tidak luput dari perhatian bangsa asing. Pada 1522, Kerajaan Sunda bahkan menjalin aliansi dagang dengan Portugis yang datang dari Malaka. Sebagai tanda kerjasama tersebut, dibangunlah prasasti Padrão di tepi pelabuhan. Artefak ini menjadi bukti fisik dari interaksi awal Nusantara dengan kekuatan Eropa, jauh sebelum kolonialisme secara penuh masuk ke wilayah ini.
Jayakarta: Lahir dari Kemenangan Fatahillah
Namun masa kejayaan Sunda Kelapa berubah drastis pada 22 Juni 1527. Pasukan dari Kesultanan Demak dan Cirebon, yang dipimpin oleh Pangeran Fatahillah, menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan ini bukan sekadar konflik militer, melainkan bagian dari perjuangan menahan laju dominasi Portugis dan memperluas pengaruh Islam di Jawa bagian barat. Setelah berhasil mengusir Portugis, Fatahillah mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta, yang secara harfiah berarti “kemenangan mutlak”.
Pergantian nama ini bukan hanya simbol kemenangan militer, tetapi juga penegasan identitas dan kedaulatan baru. Jayakarta lalu berkembang menjadi kota pelabuhan yang tetap ramai, sekaligus benteng strategis bagi kekuasaan Islam di kawasan pesisir. Dalam catatan sejarah Belanda dan Portugis, nama Jayakarta mulai muncul sebagai kota yang diperhitungkan dalam jaringan pelayaran internasional.
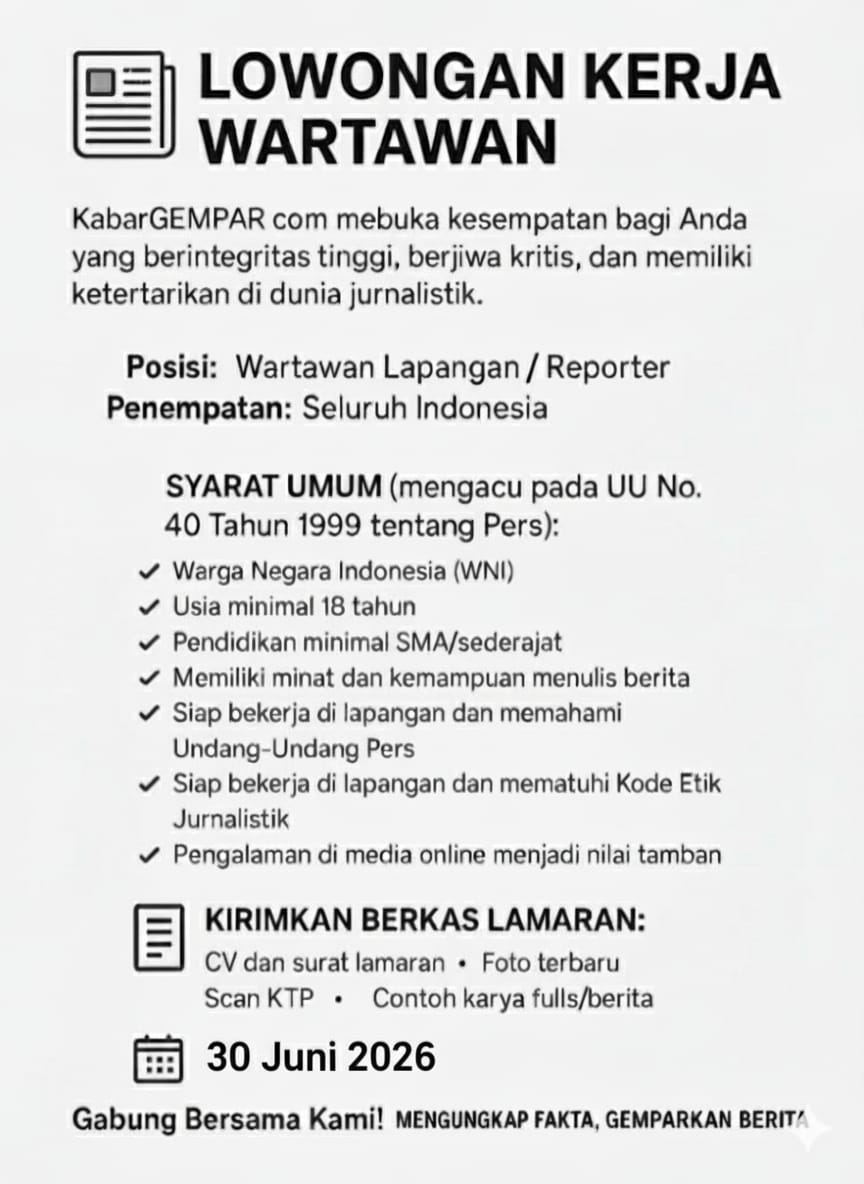
Batavia: Kota Kolonial Gaya Eropa
Jayakarta tidak bisa bertahan lama dalam ketenangan. Sekitar satu abad setelah Fatahillah menaklukkan kota, bangsa Belanda datang dengan niat membangun imperium dagangnya di Asia. Tahun 1619 menjadi momen penting ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen menyerang Jayakarta. Kota itu dibakar habis, penduduknya diusir, dan di atas puing-puingnya Belanda mendirikan kota baru bernama Batavia.
Batavia dirancang dengan arsitektur dan tata kota bergaya Belanda klasik. Kanal-kanal dibuat menyusuri jalan utama, dinding dan benteng kokoh dibangun mengelilingi kota. Gedung-gedung seperti Stadhuis (Balai Kota), Gereja Sion, dan Kasteel Batavia menjadi simbol kekuasaan kolonial. Namun di balik kemegahan itu, Batavia juga menyimpan sisi kelam. Segregasi rasial sangat kuat; warga Eropa hidup di dalam kota, sementara warga Tionghoa, Jawa, dan pribumi lainnya tinggal di luar tembok kota dengan kondisi yang jauh berbeda. Kanal-kanal yang awalnya dibuat untuk keindahan dan transportasi, berubah menjadi sarang penyakit tropis yang membuat Batavia dijuluki “kuburan orang Eropa”.
Djakarta: Masa Pendudukan Jepang dan Gejolak Baru
Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda terguncang hebat ketika Perang Dunia II pecah di Pasifik. Pada Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia dan mengganti namanya menjadi Djakarta Tokubetsu Shi, atau Kota Khusus Jakarta. Meski pendudukan ini hanya berlangsung selama tiga tahun, dampaknya sangat besar dalam mendorong semangat nasionalisme. Jepang membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan, sekaligus membentuk organisasi-organisasi semi-militer seperti PETA (Pembela Tanah Air).
Masa ini juga menjadi masa yang penuh penderitaan. Rakyat mengalami kelaparan, kerja paksa, dan pembatasan ekstrem. Namun, pengalaman tersebut turut membentuk kesadaran kebangsaan yang kuat di kalangan rakyat Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, momen itu dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk menyatakan kemerdekaan.
Proklamasi dan Kembali Menjadi Ibukota
Pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jakarta menjadi saksi bisu lahirnya negara baru setelah berabad-abad dijajah oleh bangsa asing. Namun perjuangan belum selesai. Belanda yang kembali ke Indonesia memicu konflik militer yang dikenal sebagai Agresi Militer I dan II.
Karena situasi di Jakarta tidak kondusif, pada 4 Januari 1946, pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta yang lebih aman. Di sanalah roda pemerintahan dijalankan hingga pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Setelah itu, Jakarta kembali berfungsi sebagai ibu kota dan pada tahun 1966, secara resmi ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia oleh pemerintah.
Jakarta Hari Ini: Kota Penuh Kontras dan Warisan
Kini, Jakarta berdiri sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat segalanya: pemerintahan, bisnis, budaya, dan pendidikan. Kota ini memiliki luas sekitar 7.659 km², terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, serta terbagi dalam 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Di balik hiruk-pikuk dan kemacetan, Jakarta tetap menyimpan banyak warisan sejarah.
Kota Tua, bekas pusat Batavia, masih berdiri meski menua. Di sana terdapat Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan gedung-gedung tua yang menjadi saksi perjalanan kota ini. Tak jauh dari pusat kota, berdiri Pasar Tanah Abang, yang dibuka pada 1935 dan kini menjadi pasar grosir terbesar di dunia. Jakarta juga memiliki Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), yang dibangun pada 1962 dengan kapasitas awal 100.000 orang, sebagai simbol kemajuan olahraga nasional.
Yang menarik, kota ini telah berganti nama lebih dari 10 kali—dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Djakarta, hingga akhirnya menjadi Jakarta. Sebuah transformasi identitas yang jarang dialami kota lain di dunia.
Merawat Sejarah, Menata Masa Depan
Sejarah Jakarta bukan hanya deretan peristiwa, tetapi juga potret dari dinamika bangsa yang terus bergerak. Kota ini adalah ruang yang merekam kolonialisme, perlawanan, nasionalisme, dan pembangunan. Setiap nama yang pernah disandangnya merepresentasikan babak perjuangan yang berbeda.
Sebagai ibu kota, Jakarta tidak sekadar menjadi pusat administratif. Ia adalah lambang dari perjuangan, keberagaman, dan impian Indonesia. Oleh karena itu, merawat sejarah Jakarta bukan tugas sejarawan semata, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dari masa lalu yang penuh liku, mari kita menata masa depan Jakarta yang lebih inklusif, manusiawi, dan lestari.
Sumber Referensi:
Arsip Museum Sejarah Jakarta
Situs Resmi DPRD DKI Jakarta
Catatan Sejarah VOC dan Belanda



